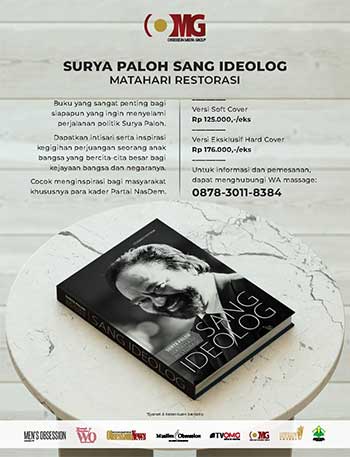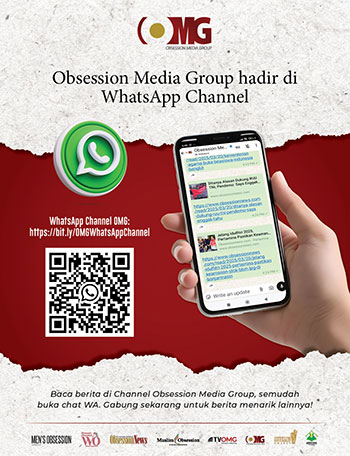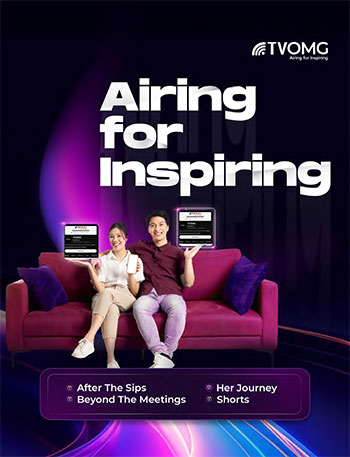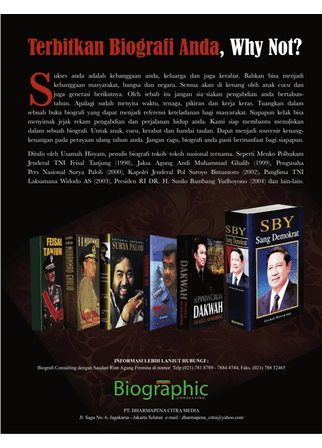Pahlawan-pahlawan Terlupakan
By Andi Nursaiful (Administrator) - 10 November 2013 | telah dibaca 12839 kali
Pahlawan-pahlawan Terlupakan
 Naskah: Andi Nursaiful/berbagai sumber Foto/Ilustrasi: Dok. MO
Naskah: Andi Nursaiful/berbagai sumber Foto/Ilustrasi: Dok. MO
Pahlawan kita pahami sebagai orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk tujuan-tujuan besar, membentuk dan mempertahankan Negara. Oleh sebab itu, mereka dianugerahi gelar kepahlawanan dan diperingati jasanya saban tahun.
Akan tetapi, gelar tak selalu menghadirkan pahlawan yang sesungguhnya. Tak sedikit pahlawan sejati yang terlupakan, bahkan sengaja diburamkan dalam sejarah. Memperingati hari Pahlawan, 10 November 1945, tulisan utama kali ini mengangkat pahlawan-pahlawan terlupakan yang belum mendapat tempat dalam catatan sejarah.
Pahlawan adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya, telah berdamai dengan kepentingan pribadinya. Apapun latar belakang dan keyakinannya, tujuan mereka tetap tunggal: membentuk negara yang kini kita kenal dengan Republik Indonesia.
 Dalam catatan sejarah nasional, begitu banyak pahlawan dan orang-orang besar yang sangat berjasa bagi lahirnya bangsa dan Negara ini. Tapi tak sedikit pula yang tenggelam dalam penulisan sejarah.
Dalam catatan sejarah nasional, begitu banyak pahlawan dan orang-orang besar yang sangat berjasa bagi lahirnya bangsa dan Negara ini. Tapi tak sedikit pula yang tenggelam dalam penulisan sejarah.
Ada yang terlambat disadari perannya, bahkan ada yang sengaja diburamkan perjuangannya. Baik itu mereka yang berjuang melawan kolonialisme, kaum pergerakan kebangsaan, para pejuang revolusi, hingga mereka yang merelakan hidup demi mempertahankan kemerdekaan.
Umumnya, mereka yang sengaja dihapus dalam catatan sejarah adalah orang-orang yang dianggap membangkang dan melawan pemerintahan yang terbentuk kemudian. Sebagian lainnya dianggap terlibat pada hal-hal yang berbau kiri. Meskipun, sesungguhnya, Indonesia dibentuk dengan cita-cita sosialisme.
Berikut ini adalah sejumlah tokoh yang kami nilai pantas mendapat tempat dalam tinta emas sejarah nasional Indonesia.
* Artikel ini dimuat pada Majalah Men's Obsession, Edisi 118, November 2013
Tirto Adhi Soerjo
Nama ini adalah salah satu sosok yang paling disembunyikan perannya dalam sejarah nasional, khususnya sejarah kebangkitan nasional. Sungguh ironis, mengingat dia adalah sosok paling penting bagi bangkitnya pergerakan kaum terdidik Indonesia.
Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo (TAS), pertama-tama harus diletakkan dalam setting sosial pergerakan nasional bangkitnya pers pribumi, pintu gerbang bagi kaum terjajah ke alam demokrasi modern. Dan TAS-lah sang pemulanya. Tulisan-tulisannya yang tajam memprovokasi kaum terjajah untuk bangkit dan berani melawan kesewenangan kolonial untuk menjadi kaum mardika.
TAS adalah tokoh idola Pramoedya Ananta Toer, penulis besar yang beberapa kali dinominasikan meraih nobel kesusastraan. Segenap kekagumannya pada sang tokoh ia tuangkan dengan menulis Sang Pemula dan tetralogi Pulau Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Dalam roman sejarah tetralogi Pulau Buru itu, TAS menjadi tokoh sentral dengan nama Minke.
Sesungguhnya, TAS adalah pemula bagi banyak hal. Ia adalah perintis pers pribumi (Medan Prijaji), ia juga pribumi pertama yang mendirikan NV (dalam bentuk perniagaan), percetakan, hotel, lembaga bantuan hukum, lembaga penyalur tenaga kerja, hingga merintis bidang periklanan.
Ia pula yang merintis gerakan emansipasi perempuan, sekaligus pendiri Sarekat Prijaji dan SDI (Serikat Dagang Islam, cikal bakal Serikat Islam), organisasi-organisasi modern pribumi pertama dan terbesar di Indonesia, bahkan lebih awal dari Boedi Oetomo.
Lahir di Blora pada 1880, meskipun berasal dari keluarga aristokrat Jawa, TAS sangat berbeda dengan kebanyakan kaum priyayi pada masanya, yang cenderung mencari aman dan menikmati keistimewaan dengan berpihak pada kolonial.
Pendidikan Eropa yang diperoleh Djokomono, begitu nama kecilnya, membuatnya mampu membandingkan kultur kasta bangsawannya, yang ia anggap kuno dan menindas, dengan kultur modern yang membebaskan.
Ia sebenarnya tak banyak mengenal kedua orang tuanya. Sebaliknya, ia mengagumi sosok sang nenek yang gagah berani menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memprotes ketidakadilan yang ditimpakan pada suaminya, seorang Bupati di Bojonegoro. Dari sang nenek pula ia mendapat petuah untuk percaya pada kekuatan sendiri, tak takut pada kemiskinan dan kehilangan pangkat.
Sikap TAS yang berbeda dari watak kebanyakan kastanya: bicara lugas, berani menentang ketidakadilan, membuatnya tersisih dari pergaulan saudara-saudaranya. Terutama, setelah ia menolak mentah-mentah meneruskan jabatan bapaknya.
Dengan pena, TAS mampu menyadarkan bangsanya. Di tangannya, pers menjelma menjadi senjata pembela keadilan. Dalam Zaman Bergerak, Takashi Shiraishi menyebut TAS sebagai bumiputra pertama yang menggerakkan bangsa melalui tulisan. Dan dengan organisasi, TAS merintis kebangkitan nasional dan memulai proses pemerdekaan.
Sungguh ironis bahwa peran TAS yang begitu besar, sukses diburamkan oleh propanda pemerintah kolonial, dan berlanjut hingga masa Orde Baru. Lebih mengenaskan lagi, setelah menderita sakit bertahun-tahun ia meninggal dalam sepi pada 7 Desember 1918.
Tak ada yang pernah memeriksa, sekalipun kawan-kawan dekatnya adalah dokter-dokter termahsyur pada masanya. Ia terlunta-lunta, sendiri, tak punya sanak saudara, bahkan makamnya pun dilupakan.
Propaganda kolonial yang menyebutnya sangat berbahaya, membuat semua sahabatnya menjauh. Satu-satunya muridnya, Mas Marco, menulis, “Jenasahnya diusung oleh rombongan sangat kecil ke peristirahatan terakhirnya di Mangga Dua. Tak satupun koran memuat kabar kematiannya. Ia benar-benar telah dilupakan oleh bangsanya, yang dicintai, dan dididiknya untuk maju.”
Sementara Pramoedya dalam Sang Pemula menulis, “Seperti jamak menimpa seorang pemula, terbuang setelah madu mulia habis terhisap. Sekiranya ia tak memulai tradisi menggunakan pers sebagai alat perjuangan dan pemersatu dalam masyarakat heterogen seperti Hindia, bagaimana sebuah nation seperti Indonesia akan terbentuk?”
Di masa Orde Baru, buku-buku Pramoedya yang mencoba meluruskan sejarah, dilarang beredar, sehingga nama TAS pun terus disembunyikan. Barulah pada 1973, pemerintah mengangkat TAS sebagai Bapak Pers Nasional. Kemudian pada pemerintahan SBY di tahun 2006, TAS diberi gelar pahlawan nasional, penghargaan yang sudah sangat terlambat.
Tan Malaka
 Buku karya Harry Poeze mungkin yang paling terang menggambarkan sosok sekaligus nasib tokoh besar satu ini. Buku tiga jilid berjudul Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949 (terbit 8 Juni 2007 di Belanda), ini, menggunakan dokumen Indonesia, Belanda, hingga arsip Rusia sebagai referensi penulisan salah satu tokoh revolusi kiri, Tan Malaka.
Buku karya Harry Poeze mungkin yang paling terang menggambarkan sosok sekaligus nasib tokoh besar satu ini. Buku tiga jilid berjudul Dihujat dan Dilupakan: Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia 1945-1949 (terbit 8 Juni 2007 di Belanda), ini, menggunakan dokumen Indonesia, Belanda, hingga arsip Rusia sebagai referensi penulisan salah satu tokoh revolusi kiri, Tan Malaka.
Tan Malaka memang justru sangat berkibar di Eropa ketimbang di negerinya sendiri. Tak heran jika Poeze, peneliti senior sekaligus Direktur KITLV Belanda, menulis disertasi mengenai Tan Malaka pada tahun 1976, lalu menulis buku kisah perjalanan hidup Tan Malaka hingga akhir hayatnya pada 1949, termasuk mengungkap lokasi tewasnya Tan Malaka di Jawa Timur, dan juga penembaknya.
Apa yang membuat Tan Malaka begitu menarik? Itu semua lantaran kisah perjuangannya yang sungguh luar biasa untuk kemerdekaan Tanah Air-nya, namun justru berujung pada pembunuhan oleh bangsanya sendiri. Padahal, lebih dari tiga dekade Tan Malaka mencoba merealisasikan gagasannya dalam kancah perjuangan Indonesia. Perjuangannya bersifat lintas bangsa dan lintas benua.
Lahir di Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, pada 1896, Sutan Ibrahim bergelar Datuk Tan Malaka menempuh pendidikan Kweekschool di Bukittinggi sebelum melanjutkan pendidikan ke Belanda. Pulang ke Indonesia tahun 1919 ia bekerja di perkebunan Tanjung Morawa, Deli.
 Penindasan terhadap buruh membuatnya berhenti dan pindah ke Jawa tahun 1921. Ia mendirikan sekolah di Semarang dan kemudian di Bandung. Aktivitasnya menyebabkan ia diasingkan ke negeri Belanda. Ia lantas pergi ke Moskwa dan bergerak sebagai agen komunis internasional (Komintern) untuk wilayah Asia Timur. Namun, ia berselisih paham karena tidak setuju dengan sikap Komintern yang menentang pan-Islamisme.
Penindasan terhadap buruh membuatnya berhenti dan pindah ke Jawa tahun 1921. Ia mendirikan sekolah di Semarang dan kemudian di Bandung. Aktivitasnya menyebabkan ia diasingkan ke negeri Belanda. Ia lantas pergi ke Moskwa dan bergerak sebagai agen komunis internasional (Komintern) untuk wilayah Asia Timur. Namun, ia berselisih paham karena tidak setuju dengan sikap Komintern yang menentang pan-Islamisme.
Ia berjuang menentang kolonialisme tanpa henti selama 30 tahun, dari Pandan Gadang, Bukittinggi, Batavia, Semarang, Yogya, Bandung, Kediri, Surabaya, hingga Amsterdam, Berlin, Moskow, Amoy, Shanghai, Kanton, Manila, Saigon, Bangkok, Hongkong, Singapura, Rangon, dan Penang. Tan Malaka sesungguhnya seorang pejuang Asia sekaliber Jose Rizal (Filipina) dan Ho Chi Minh ( Vietnam).
Tan Malaka sesungguhnya menentang rencana pemberontakan PKI yang meletus pada 1926/1927 sebagaimana ditulisnya dalam buku Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia, Kanton, April 1925, dan dicetak ulang di Tokyo, Desember 1925). Perpecahan dengan Komintern mendorong Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, Juni 1927.
Setelah Indonesia merdeka, perjuangan Tan Malaka mengalami pasang surut. Pada 1948, Tan Malaka menentang diplomasi dengan Belanda karena dianggap Indonesia dalam posisi dirugikan. Ia memimpin Persatuan Perjuangan yang menghimpun 141 partai/organisasi masyarakat dan laskar, menuntut agar perundingan baru dilakukan jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia seratus persen.
 Setahun kemudian, tahun 1949, Tan Malaka ditembak mati. Ia disergap di Dusun Tunggul, Desa Selopanggung, di kaki Gunung Wilis, dan ditembak oleh Suradi Tekebek atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.
Setahun kemudian, tahun 1949, Tan Malaka ditembak mati. Ia disergap di Dusun Tunggul, Desa Selopanggung, di kaki Gunung Wilis, dan ditembak oleh Suradi Tekebek atas perintah Letnan Dua Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.
Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno memberi gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka. Namun, sejak era Orde Baru, namanya dihapus dalam pelajaran sejarah meski gelar itu tidak pernah dicabut. Ia dianggap tokoh PKI dan dituduh terlibat pemberontakan beberapa kali. Padahal, Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI tahun 1926/1927. Ia sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Bahkan, partai yang didirikan pada 7 November 1948, Murba, dalam berbagai peristiwa justru berseberangan dengan PKI.
Yang tak terbantahkan, Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang sangat bersikukuh bahwa pendidikan rakyat adalah cara terbaik membebaskan rakyat dari kebodohan dan keterbelakangan demi membebaskan diri dari kolonialisme. Tan Malaka dan gagasannya tidak hanya menjadi penggerak rakyat Indonesia, tetapi juga membuka mata rakyat Philipina dan semenanjung Malaya, atau bahkan di belahan dunia lain.
dr. Radjiman Wedyodiningrat
 Ia memang tidak seterkenal dan sefenomenal tokoh-tokoh besar sekelas Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Sudirman, bahkan Pangeran Diponegoro. Tapi perjuangan dan jasanya sangat besar, terlebih saat-saat menjelang Indonesia merdeka.
Ia memang tidak seterkenal dan sefenomenal tokoh-tokoh besar sekelas Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Sudirman, bahkan Pangeran Diponegoro. Tapi perjuangan dan jasanya sangat besar, terlebih saat-saat menjelang Indonesia merdeka.
dr. Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Radjiman Wedyodiningrat, lahir di Yogyakarta pada 21 April 1879, datang dari keluarga rakyat biasa. Meski begitu, ia tak patah semangat untuk mengenyam pendidikan hingga berhasil menjadi dokter. Radjiman adalah dokter sekaligus tokoh pergerakan. Perannya sangat menonjol menjelang kemerdekaan Indonesia. Khususnya ketika bangsa Indonesia sedang merumuskan dasar negara yang akhirnya disebut Pancasila.
Peran dan jasanya dianggap setara dengan Bung Karno, Bung Hatta, Mohammad Yamin, Dr. Wahidin Sudiro Husodo, HOS Cokroaminoto, dan sejumlah pahlawan nasional lainnya.Atas berbagai jasanya, ia banyak diusulkan oleh berbagai pihak untuk menjadi pahlawan nasional.
Radjiman tercatat sebagai satu-satunya orang yang terlibat secara akif dalam kancah perjuangan sejak munculnya Boedi Utomo hingga pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKl). Puncak peranannya, ketika ia dipercaya menjadi Ketua BPUPKl.
Pada awal kemerdekaan, Radjiman juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kemudian anggota Dewan Pertimbangan Agung RI. Dalam perkembangannya, seluruh badan perwakilan, baik yang didirikan RI maupun Belanda digabung dalam DPR-RI. Sebagai anggota tertua, Radjiman mendapat kehormatan memimpin rapat pertama lembaga itu.
Radjiman wafat pada 20 September 1952 di Dirgo, Widodaren, Ngawi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Mlati, Sleman, Yogyakarta, berdekatan dengan makam Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah membesarkannya.
Mas Marco Kartodikromo
 Inilah murid utama Tirto Adhi Soerjo (TAS), baik dalam dunia jurnalistik perjuangan maupoun sebagai tokoh pergerakan kebangkitan nasional. Seperti TAS, Mas Marco juga berjuang dengan penanya untuk menyadarkan bangsanya untuk bangkit merdeka.
Inilah murid utama Tirto Adhi Soerjo (TAS), baik dalam dunia jurnalistik perjuangan maupoun sebagai tokoh pergerakan kebangkitan nasional. Seperti TAS, Mas Marco juga berjuang dengan penanya untuk menyadarkan bangsanya untuk bangkit merdeka.
Dalam salah satu tulisannya pada di harian Panca Warta, awal Februari 1917, Sama Rata-Sama Rasa, ia menuntut persamaan hak kaum bumiputera dan orang Eropa. Membuatnya ditangkap pemerintah kolonial. Seperti tokoh pergerakan lain, Marco juga sudah langganan keluar masuk penjara dan lokasi pengasingan.
Pada masanya, Marco merupakan salah satu tokoh kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarawan Jepang-Amerika Takashi Shirashi pernah menuliskan masalah ini. Jika kemudian ideologi Marco memilih lebih ke kiri, bukan berarti jasa-jasanya kepada bangsa ini hilang. Bukan berarti harus meniadakan pengorbanan serta perlawanan pada kolonial Belanda. Ia menjadi salah satu simbol perjuangan sejati melawan penjajahan di masanya.
Marco dilahirkan menjelang akhir abad 19 di Cepu, Jawa Tengah. Pendidikannya terbatas pada Sekolah Rakyat, tetapi belajar bahasa Belanda secara otodidak dan membaca banyak literatur Barat.
Ia terjun ke dunia pergerakan pada usia 22 tahun. Ketika Dr. Cipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke pengasingan pada 1913, kemarahannya memuncak lalu mendirikan Indlandsche Journalisten Bond (Surakarta 1914) dan surat kabar Doenia Bergerak sebagai alat untuk menyampaikan gagasan perjuanganya dengan moto: Berani karena benar, takut karena salah.
 Setelah keluar dari penjara untuk keempat kalinya, ia bergabung dengan Sarekat Islam Semarang yang terpecah menjadi dua, Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah yang berhaluan sosialis. Marco memilih Sarekat Islam Merah yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Setelah keluar dari penjara untuk keempat kalinya, ia bergabung dengan Sarekat Islam Semarang yang terpecah menjadi dua, Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah yang berhaluan sosialis. Marco memilih Sarekat Islam Merah yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pasca gagalnya pemberontakan komunis pada 1927, Marco dibuang ke Boven Digoel, Papua. Di tempat pembuangan ia dikenal sebagai orang yang paling bandel dan anti-Belanda, sehingga diasingkan ke Gudang Arang, sebuah daerah yang sangat ganas kondisi alamnya.
Marco meninggal di pembuangan pada 1932 dan tetap sebagai orang yang tidak mau kompromi dengan penjajah. Bahkan Gubernur Jenderal Belanda pun ia tolak mentah-mentah saat minta bertemu dengannya.
Maruto Nitimihardjo dan Pandu Kartawiguna
 Inilah tokoh Partai Murba yang paling diingat di samping nama Sukarni. Padahal, Maruto adalah salah satu pusar dari seluruh rangkaian gerakan muda di Indonesia dalam kurun waktu 1926-1950.
Inilah tokoh Partai Murba yang paling diingat di samping nama Sukarni. Padahal, Maruto adalah salah satu pusar dari seluruh rangkaian gerakan muda di Indonesia dalam kurun waktu 1926-1950.
Maruto adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap Sumpah Pemuda 1928, dialah yang mendorong PPPI (Persatuan Peladjar-Peladjar Indonesia) Sugondo Djojopuspito untuk melakukan gebrakan politik dengan membangun jaringan. Ide itu kemudian disetujui oleh Kotjo Sungkono, Ketua PI (Pemuda Indonesia) yang merupakan sayap penting di dalam tubuh PPPI.
Ide Maruto ini disambut antusias oleh Mohammad Yamin. Bersama Sugondo dan Yamin, Maruto lantas menemui Bung Karno di Bandung untuk menyampaikan ide yang juga disambut antusias itu.
Sesungguhnya, Maruto bukan sosok penuh ide atau cerdas. Tidak seperti Yamin yang pengkhayal, atau Sjahrir yang teramat cerdas. Kelebihan Maruto adalah kemampuan dan ketekunan membangun jaringan. Seperti Yamin, Maruto terobsesi membangun gerakan muda menuju era kemerdekaan, terutama setelah membaca buku Tan Malaka, Naar de Republiek (Menuju Negara Republik).
Bila Sukarno, Hatta, atau Tan Malaka adalah aktor-aktor panggung sejarah, maka Maruto adalah sosok yang berkeringat membereskan segala perabot panggung. Lewat jaringan gerakan di daerah yang dibangunnya, Sumpah Pemuda 1928 bisa berjalan lancar. Bahkan tokoh penting Aceh, Daud Bereuh, yang pernah melawan Sukarno, mau hadir berkat Maruto. Ia pula yang memberesekan konflik Daud Bereuh dengan Presiden Soekarno.
Pandu Kartawiguna
Selain itu, Maruto bersama Pandu Kartawiguna, dikenal sebagai motor perang revolusi di Jakarta dengan memutuskan angkat senjata dengan pihak asing ketimbang berunding. Karena sikap itu, Maruto dan Pandu diusir oleh anggotan Prapatan 10 pimpinan Eri Soedewo yang lebih ingin melalui jalan diplomasi. Pengusiran ini memancing tumbuhnya laskar radikal yang angkat senjata di seputar Jakarta dan menjadikan Revolusi 1945 jadi perang fisik.
Bersama Maruto, Pandu yang mendirikan kantor berita Antara bersama Adam Malik, menggiring pemuda-pemuda untuk membangun benteng-benteng pasir di sekitar wilayah Cikini, Pegangsaan, hingga Kramat Raya, sebagai basis pertempuran.
Wikana dan Sukarni
 Namanya nyaris tak pernah didengar. Padahal, Wikana adalah orang yang paling memperhitungkan posisi kemerdekaan Indonesia, justru saat Soekarno dan Hatta sangat percaya pada janji Jepang. Padahal bila diberi hadiah kemerdekaan oleh Jepang, Indonesia akan jadi “wilayah tanpa tuan.” Sebab, apapun pemberian Jepang, bisa dibatalkan demi hukum karena Jepang kalah perang.
Namanya nyaris tak pernah didengar. Padahal, Wikana adalah orang yang paling memperhitungkan posisi kemerdekaan Indonesia, justru saat Soekarno dan Hatta sangat percaya pada janji Jepang. Padahal bila diberi hadiah kemerdekaan oleh Jepang, Indonesia akan jadi “wilayah tanpa tuan.” Sebab, apapun pemberian Jepang, bisa dibatalkan demi hukum karena Jepang kalah perang.
Dalam pikiran Wikana, satu-satunya jalan adalah merebut kemerdekaan dari Jepang. Perhitungannya, jika Indonesia kembali diterima sekutu, maka sama saja dengan peristiwa 1811 di mana Inggris merebut Jawa dari Perancis kemudian mengembalikannya kepada Belanda. Sementara dua Raja di Jawa tidak segera melakukan pemberontakan, melainkan main intrik sendiri. Akhirnya Jawa kembali dijajah Belanda.
Wikana merasa tahu persis bahwa Jepang tidak akan bertindak apapun. Seluruh perwira Jepang satu persatu sudah bunuh diri dan kehilangan harapan. Mereka akan membiarkan saja apapun gerakan dari Indonesia. Wikana mengetahui itu karena dia bekerja di Kaigun, atau Dinas Angkatan Laut Jepang.
Wikana lantas menyampaikan ide ini (merebut kemerdekaan) kepada Sukarni yang dikenal memiliki jaringan ke pemuda. Sukarni kemudian mendesak untuk memerdekakan sendiri, atau bekerjasama dengan Sjahrir, bukan dengan Sukarno yang dianggap kolaborator Jepang kala itu.
Awalnya Wikana setuju ide Sukarni, tapi Sjahrir cukup gentar saat akan menerima tanggung jawab Proklamasi. Sjahrir pun mendatangi Maruto, dan berulang kali bertanya “apa saya bisa?”
Mendengar keraguan Sjahrir, tak ada jalan lain bagi Wikana untuk mendesak Soekarno-Hatta. Wikana pun datang bersama Chaerul Saleh, Sukarni, Subadio, dan lainnya termasuk DN Aidit (kelak jadi tokoh penting PKI). Di sana Wikana yang paling dituakan dari pemuda untuk bicara, tapi Sukarno bicara terlalu keras pada Wikana sampai membentaknya. Inilah yang membuat kecewa Sukarni, seorang pemuda Blitar berhati panas. Sepulangnya dari rumah Sukarno, muncul ide Sukarni untuk menculik Sukarno dan memaksa usulan Wikana diterima.
Soekarno-Hatta pun diculik dan dibawa ke Rengasdengklok. Tapi sebelumnya, Wikana sudah mendesak Achmad Subardjo untuk merayu Soekarno jangan melakukan proklamasi buatan Jepang. Berkali-kali Hatta bergumam “t\Tidak mungkin melakukan ini tanpa Jepang, kita belum siap jika harus perang dengan Jepang.” Sukarni bersikeras, jalan satu-satunya adalah Indonesia melakukan sendiri, dan berperang dengan Jepang adalah resiko.
Ternyata lobi Subardjo berhasil, Laksamana Maeda berhasil dibujuk untuk pasang badan melindung Sukarno-Hatta dan para pemuda untuk melakukan proklamasi yang bukan buatan Jepang.
Sukarni
 Adapun Sukarni, yang juga menjadi pengikut paling setia Tan Malaka, pantas diibaratkan api gerakan pemuda yang selalu membangkitkan semangat. Tanpa Sukarni, gerakan muda Indonesia saat itu mungkin ntidak memiliki daya katalisatornya. Dialah penghubung agar gerakan menjadi hidup.
Adapun Sukarni, yang juga menjadi pengikut paling setia Tan Malaka, pantas diibaratkan api gerakan pemuda yang selalu membangkitkan semangat. Tanpa Sukarni, gerakan muda Indonesia saat itu mungkin ntidak memiliki daya katalisatornya. Dialah penghubung agar gerakan menjadi hidup.
Sukarni pula yang memaksa Soekarno untuk bertaruh di Lapangan Ikada agar ia dipercaya rakyat dan dilihat oleh intel-intel sekutu, bahwa dialah pemimpin negeri ini. Aksi Sukarni sering membuat kesal Sukarno dan pemerintahannya karena dianggap selalu menempuh jalan bahaya.
Tapi aksinya yang nekat, seperti pemaksaan pidato di Lapangan Ikada, ternyata membuahkan hasil hebat. Sejak Lapangan Ikada, Soekarno memperoleh legitimasi politik luar biasa dari rakyat. Dan Soekarno mengakui itu dengan mendirikan Monumen Nasional. Pada hakikatnya jika Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah de jure, maka Pidato Lapangan Ikada adalah de facto Kemerdekaan Indonesia.
Chaerul Saleh dan Kasman Singodimedjo
 Chaerul Saleh adalah tokoh yang hidup hanya demi prinsipnya, dan mati dalam tragedi. Di masa revolusi 1945, perannya sangat penting. Perang Kemerdekaan terjadi bukan karena perlawanan tentara resmi, tapi karena nekatnya tokoh-tokoh muda. Peranannya tak jauh beda dengan yang dilakukan Wikana. Ia juga seseorang yang banyak akal, termasuk mengusahakan mobil untuk Soekarno, dan mengurusi semua persiapan.
Chaerul Saleh adalah tokoh yang hidup hanya demi prinsipnya, dan mati dalam tragedi. Di masa revolusi 1945, perannya sangat penting. Perang Kemerdekaan terjadi bukan karena perlawanan tentara resmi, tapi karena nekatnya tokoh-tokoh muda. Peranannya tak jauh beda dengan yang dilakukan Wikana. Ia juga seseorang yang banyak akal, termasuk mengusahakan mobil untuk Soekarno, dan mengurusi semua persiapan.
Di saat Hatta mundur karena bertanggung jawab terhadap pembatalan bayar hutang KMB 1949, Chaerul diangkat menjadi menteri, dan dialah konseptor pembangunan yang mengadopsi strategi Jerman Barat dengan membangun industri-industri besar seperti Krakatau Steel dan Pupuk Sriwijaya. Ia melakukan lobi-lobi ke Uni Soviet untuk membantu pembangunan Krakatau Steel.
Setelah peristiwa Gestapu 65, Chaerul habis-habisan berdiri di belakang Soekarno. Ia menolak Soeharto, walaupun Partainya, Murba, memutuskan mendukung. Chaerul ditangkap dan kemudian dipenjarakan, lalu meninggal tak jelas di dalam penjara.
 Kasman Singodimedjo
Kasman Singodimedjo
Kasman adalah salah satu tokoh pergerakan nasional. Tokoh muda dari kalangan Islam nasionalis ini sangat mewarnai hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, aktivis Muhammadiyah kelahiran Purworejo itu, selalu tampil sebagai perintis di saat-saat kritis.
Pascakemerdekaan, Kasman pernah menjabat Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Jaksa Agung, Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi Kementerian Pertahanan, Kepala Kehakiman dan Pengadilan Militer Kementerian Pertahanan, dan terakhir Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II.
Pemikiran politik dan kenegaraan Kasman, tak lepas dari keyakinan dan pendidikan Islam yang diperolehnya sejak kecil, baik dari ayahnya, maupun tokoh-tokoh Islam seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Abdul Aziz. Salah satu pemikirannya, menolak istilah demokrasi dan mengajak menggunakan musyawarah.
RMP Sosrokartono dan Kiai Wahab Hasbullah
 Nama RMP Sosrokartono tak seharum RA Kartini, adik kandung sekaligus sahabat dalam berbagi ilmu dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lahir di Jepara pada 10 April 1877, Sosrokartono tumbuh sebagai seorang intelektul, yang menurut Bung Hatta, bahkan seorang yang jenius.
Nama RMP Sosrokartono tak seharum RA Kartini, adik kandung sekaligus sahabat dalam berbagi ilmu dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lahir di Jepara pada 10 April 1877, Sosrokartono tumbuh sebagai seorang intelektul, yang menurut Bung Hatta, bahkan seorang yang jenius.
Sosrokartono adalah mahasiswa Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri, sebelum generasi Bung Hatta. Dengan menggenggam gelar Docterandus in de Oostersche Talen dari Perguruan Tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa dan menjelajahi berbagai pekerjaan.
Pada tahun 1917, ia diterima oleh harian The New York Herald Tribune, sebagai wartawan peliput Perang Dunia I. Itu antara lain karena ia menguasai 17 bahasa, termasuk 10 bahasa suku di negerinya. Sebelumnya ia banyak menjadi penterjemah di Wina, Austria, dan dikenal sebagai sang Jenius dari Timur.
Meski dikenal dekat dengan bangsawan Belanda, Sosrokartono adalah salah satu pembimbing Kartini dalam menuliskan surat keprihatinannya akan nasib pendidikan warga pribumi. Pada 29 Agustus 1899 dalam Kongres ke-25 Bahasa dan Sastra Belanda di Gent, Belgia, Sosrokartono menyampaikan pidato yang menggemparkan.
Sosrokartonolah yang menginspirasi Kartini dalam memperjuangkan hak-hak pribumi. Mereka sering sekali berkirim surat dan menceritakan tentang keadaan mereka masing-masing di negeri yang saling berjauhan.
Gelar Doctorandus in de Oostersche Talen yang diterimanya, adalah tanda awal kebangkitan intelektual-modern Indonesia. Satu hal menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial sehingga dihambat untuk mencapai gelar doktor. Ia dituduh simbol kebangkitan intelektual dan nasionalisme pribumi.
 Kiai Wahab Hasbullah
Kiai Wahab Hasbullah
Dalam menghadapi perjanjian dengan Belanda yang penuh ketidakadilan, Kiai Wahab memimpin untuk melawan. Di kalangan santri, namanya sangat terkenal sebagai kiai yang gigih berjuang melawan penjajah.
Lahir di Tambakberas, Jombang pada 1888, Wahab dikenal sebagai santri berjiwa aktivis yang tak segan membela kaum lemah dan penindasan kaum penjajah. Sepulang dari Mekkah pada 1914, Wahab mengasuh pesantrennya di Tambakberas sekaligus aktif dalam pergerakan nasional. Pada 1916, ia mendirikan organisasi pergerakan yang dinamai Nahdlatul Wathon (kebangkitan negeri), dengan tujuan membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia.
Untuk memperkuat gerakannya, pada 1918 Kiai Wahab mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan saudagar) sebagai pusat penggalangan dana bagi perjuangan pengembangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari memimpin organisasi ini. Sementara Kiai Wahab menjadi Sekretaris dan bendaharanya. Pada 1926, Kiai Wahab ikut mendirikan Nahdlatul Ulama.
Masa-masa menjelang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab aktif di medan tempur dengan memimpin organisasi Barisan Kiai, organisasai yang secara diam-diam menopang Hisbullah dan Sabilillah.
Diupakan Sejarah, Dilumat Zaman
 Miris membayangkan bahwa kaki yang kini bergetar dalam melangkah itu, dan tangan yang nyaris lunglai itu, dulu pernah berdiri tegap dan mantap menggerek Sang Saka Merah Putih untuk berkibar pertama kalinya di atas Bumi Pertiwi.
Miris membayangkan bahwa kaki yang kini bergetar dalam melangkah itu, dan tangan yang nyaris lunglai itu, dulu pernah berdiri tegap dan mantap menggerek Sang Saka Merah Putih untuk berkibar pertama kalinya di atas Bumi Pertiwi.
Sulit pula membayangkan bahwa kakek berusia 80-an tahun bernama Ilyas Karim itu adalah pemuda 18 tahun bercelana pendek yang dengan mantap mengibarkan sang saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kalinya.
Kini Ilyas menghabiskan sisa hidup di rumahnya yang sangat sederhana di pinggir rel di Jalan Rawajati Barat, nomor 7, Kalibata, Jakarta Selatan. Sejarah telah melupakan dirinya, zaman telah melumat nasibnya.
Kakek kelahiran Padang Pariaman, 31 Desember 1927 itu mengisahkan, dirinya hanya mengikuti seniornya, Chairul Saleh, yang memberitahukan pemuda di Asrama Pemuda Islam (API) untuk bersiap berkumpul di rumah Bung Karno keesokan harinya.
 Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Ilyas bergegas menuju rumah Bung Karno. Setibanya di sana, tangan Ilyas tiba-tiba ditarik oleh Sudanco Latief Hendraningrat dan disuruh menjadi petugas menggerek bendera.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Ilyas bergegas menuju rumah Bung Karno. Setibanya di sana, tangan Ilyas tiba-tiba ditarik oleh Sudanco Latief Hendraningrat dan disuruh menjadi petugas menggerek bendera.
Selain menjadi salah satu tokoh bersejarah dalam pengibaran bendera Merah Putih, Ilyas mengabdikan hidupnya sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia bertugas keliling daerah sampai menjadi pasukan perdamaian di Kongo, Lebanon, dan Vietnam. Selama puluhan tahun menjadi tentara dan berpangkat terakhir Letnan Kolonel, Ilyas tak bergelimang harta. Lantai dua rumahnya hanya terbuat dari seng.
Meski hidup dalam keterbatasan, Ilyas tak mau terpuruk meratapi nasib. Ia aktif menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pejuang Siliwangi yang sering mengadakan bakti sosial bagi anak yatim. "Hidup itu untuk mengabdi bukan untuk diam-diam saja," tegasnya.
Kisah Pemikul Tandu Jendral Sudirman
Kita tahu peristiwea bersejarah ketika Jenderal Sudirman bergerilya dalam keadaan sakit dan bergerak dengan ditandu. Tandu itu sekarang dipajang di museum Satria Mandala, tapi sang pemikul tandu sama sekali dilupakan.
 Di Dusun Goliman Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, di kaki Gunung Wilis, Jawa Tengah, siapa menyangka jika kakek 80-an tahun bernama Djuwari adalah salah seorang tujuh orang pemikul tandu itu. Ia hidup berkubang kemiskinan, dan juga dilupakan sejarah.
Di Dusun Goliman Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, di kaki Gunung Wilis, Jawa Tengah, siapa menyangka jika kakek 80-an tahun bernama Djuwari adalah salah seorang tujuh orang pemikul tandu itu. Ia hidup berkubang kemiskinan, dan juga dilupakan sejarah.
Kampung Djuwari menjadi titik awal rute gerilya Sudirman dari Kediri-Nganjuk sepanjang 35 km. Dia bercerita, memanggul tandu Pak Dirman adalah kebanggaan luar biasa. Semua itu dilakukan dengan rasa ikhlas tanpa berharap imbalan apapun.
Add to Flipboard Magazine.
Popular

Wanita Muslim yang Menginspirasi Dunia
24 July 2014
Film-film Islam Terbaik Sepanjang Masa
01 July 2013