Bissu yang Kian Tergerus Zaman
By Andi Nursaiful (Administrator) - 08 October 2013 | telah dibaca 4884 kali
 Naskah: Andi Nursaiful/berbagai sumber Foto: Istimewa
Naskah: Andi Nursaiful/berbagai sumber Foto: IstimewaTertatih-tatih bertahan dalam arus modernisasi, Bissu semakin tergerus zaman, terpinggirkan, dan nyaris ditelan waktu. Padahal, dari kacamata kekayaan khazanah budaya Nusantara, manusia-manusia ‘setengah dewa’ dari Tanah Bugis, ini, seharusnya tetap eksis. Selingan kali ini mengajak Anda menjelajahi dunia Bissu, yang dipercaya sebagai satu-satunya gender ke-5 di bumi manusia.
Jika dunia hanya mengenal dua gender (laki-laki dan perempuan), maka di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, sekelompok masyarakat membagi lima gender dalam komunitas mereka. Selain pria (oroane) dan wanita (makkunrai), ada calabai (pria yang berperilaku seperti wanita), ada calalai (wanita yang berperilaku layaknya pria), dan ada pula Bissu.
Meskipun secara anatomi biologis mereka bisa wanita atau pria, namun Bissu bukanlah pria, bukan juga wanita. Mereka bukan pria manis, dan bukan pula wanita macho. Mereka dianggap mewakili semuanya, atau sebaliknya, berada ‘di luar batasan gender.’

 Sharyn Graham, seorang peneliti dari University of
Sharyn Graham, seorang peneliti dari University of Western Australia di Perth, Australia, yang menerbitkan penelitian ilmiah mengenai kaum Bissu, menjelaskan, mereka tidak dapat dianggap sebagai banci atau waria. Mereka tidak memakai pakaian dari golongan gender apapun, melainkan setelan tertentu dan tersendiri untuk golongan mereka. Mereka juga menguasai bahasa khusus, yaitu bahasa Torilangi (bahasa orang langit) yang bagi sebagian kalangan dianggap bahasa dewata. Sharyn Graham pula yang mempopulerkan Bissu sebagai gender ke-5.
Kaum Bissu, yang dalam bahasa Bugis diartikan “bersih,” memiliki derajat yang lebih tinggi dalam struktur sosiokultural masyarakat. Mereka memiliki peran ritual, menjadi jembatan komunikasi dan perantaran manusia dengan dewa, hingga berlaku sebagai penyembuh segala penyakit dan bala.
Singkatnya, mereka dipandang sebagai orang suci, pendeta, dukun, orang sakti, bahkan manusia setengah dewa yang tak mempan oleh senjata tajam dan mampu mendatangkan panen berlimpah. Itu semua bisa terjadi lantaran Bissu dipercaya telah melepaskan kodrat dan hasrat biologis mereka. Dengan melepas kodrat dan hasrat biologis, hubungan mereka dengan dewa tidak akan terputus.
Bissu hidup dalam kepercayaan tradisional komunitas kecil di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dewasa ini, hanya tersisa sedikit Bissu. Itupun dianggap tak lagi sehebat para Bissu sebelumnya. Pada Juni 2011, Bissu Puang Matoa Saidi, salah seorang dari sedikit golongan Bissu Bugis yang tersisa juga sudah meninggal.
Padahal, Puang Matoa Saidi yang bertindak sebagai pemimpin Bissu, juga dikenal sebagai satu-satunya penghafal naskah sastra Bugis, Sureq La Galigo, naskah sastra terpanjang di dunia, melebihi kisah Mahabrata dan Ramayana.
 Dalam manuskrip kuno yang mencapai 9.000 halaman folio itu, banyak menceritakan tentang kehadiran Bissu sebagai penyempurna peran dari dewa yang diturunkan dari langit (Dunia Atas) untuk memerintah di Bumi (Dunia Tengah), dan kawin dengan dewa yang dimunculkan dari lautan (Dunia Bawah). Diceritakan juga peran Bissu yang melengkapi kisah Tomanurung (manusia pertama di Bumi versi orang Bugis) dan generasi-generasi berikutnya.
Dalam manuskrip kuno yang mencapai 9.000 halaman folio itu, banyak menceritakan tentang kehadiran Bissu sebagai penyempurna peran dari dewa yang diturunkan dari langit (Dunia Atas) untuk memerintah di Bumi (Dunia Tengah), dan kawin dengan dewa yang dimunculkan dari lautan (Dunia Bawah). Diceritakan juga peran Bissu yang melengkapi kisah Tomanurung (manusia pertama di Bumi versi orang Bugis) dan generasi-generasi berikutnya. Masih dalam manuskrip sastra kuno itu, dikisahkan bahwa Bissu pertama yang ada di bumi bernama Lae-lae, yang diturunkan bersama Tomanurung. Dari sini sebagian ahli sejarah meyakini tradisi Bissu berawal dari daerah Luwu, lalu menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Mereka menyingkir dan bersembunyi di daerah Segeri ketika pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan memburu mereka untuk dibasmi.
Untuk menjadi Bissu, seseorang harus memadukan semua aspek gender. Dalam banyak contoh, ini berarti mereka harus dilahirkan dengan sifat hermaprodit atau individu interseksual. Tidak semua orang bisa dan mampu menjadi Bissu. Untuk mengikuti jalan Bissu, seseorang yang tidak dilahirkan dengan sifat hermaprodit atau individu interseksual, harus mendapatkan bisikan gaib dan perintah para dewa.
Namun itu baru tahap awal, sebab berikutnya para calon Bissu ini harus menempuh ujian berat. Selain harus mampu menekan hasrat biologis dan melepas kodrat seksualnya, mereka harus mutih (puasa) selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum.
 Sebelum diresmikan sebagai Bissu, mereka juga harus bernazar (mattinja’) untuk menjalani prosesi irebba (dibaringkan), yang dilakukan di rakkeang (loteng) bagian depan pada Bola Arajang (Rumah Pusaka). Prosesi ini berlangsung antara 3-7 hari setelah sebelumnya dimandikan, dikafani, dan dibaringkan berdasarkan hari yang dinazarkan.
Sebelum diresmikan sebagai Bissu, mereka juga harus bernazar (mattinja’) untuk menjalani prosesi irebba (dibaringkan), yang dilakukan di rakkeang (loteng) bagian depan pada Bola Arajang (Rumah Pusaka). Prosesi ini berlangsung antara 3-7 hari setelah sebelumnya dimandikan, dikafani, dan dibaringkan berdasarkan hari yang dinazarkan. Eksistensi Bissu memang sejak lama diperbincangkan para ahli sosiologi dan sejarah. Ketiadaan gender mereka, kerap diduga mirip dengan ide awal muslim tentang "Khanith" dan "Mukhannathun" yang menjadi pengawal batas-batas suci dan adanya posisi setara untuk para interseksual dan transgender yang ada dalam budaya muslim tradisional tertentu. Tetapi dalam kasus ini, budaya Bissu bersumber dari budaya Bugis kuno yang jauh lebih awal dari budaya muslim. Bissu sudah eksis sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan.
 Di masa kerajaan, Bissu menempati posisi tinggi. Umumnya mereka menjadi penasihat raja dalam berbagai hal (bukan hanya spiritual), penyambung lidah raja dengan rakyat, sekaligus bertugas menjaga dan merawat alat-alat kerajaan dan benda-benda suci yang dikeramatkan. Bahkan, Bissu dipercaya menjaga puteri raja, khususnya ketika mandi dan berganti pakaian.
Di masa kerajaan, Bissu menempati posisi tinggi. Umumnya mereka menjadi penasihat raja dalam berbagai hal (bukan hanya spiritual), penyambung lidah raja dengan rakyat, sekaligus bertugas menjaga dan merawat alat-alat kerajaan dan benda-benda suci yang dikeramatkan. Bahkan, Bissu dipercaya menjaga puteri raja, khususnya ketika mandi dan berganti pakaian.Ketika Kahar Muzakkar dan dan kelompoknya berhasil ditumpas, komunitas Bissu sempat sedikit mendapat ruang di era Orde Lama. Namun penderitaan mereka lantas berlanjut ketika resim Orde Baru (Orba) berkuasa pada 1965. Mereka dituduh penganut paham komunis dan tidak beragama. Operasi Toba (Operasi Taubat) pun digelar untuk memburu mereka.
Rezim Orba bahkan memunculkan doktrin baru dalam masyarakat bahwa barangsiapa bertemua Bissu, maka mereka akan mengalami nasib sial selama 40 hari 40 malam. Seluruh amal baik yang diperbuat selama 40 hari tidak akan diterima pahalanya oleh Tuhan YME. Tak heran jika banyak Bissu yang sebelumnya sangat dihormati, lantas menjadi sasaran lemparan batu dan olok-olokan bocah di jalanan.
Sebagian masyarakat yang masih bersimpati kepada para Bissu, pun hanya diam tanpa mampu bisa berbuat apa-apa. Hanya ada beberapa orang yang berani menyembunyikan Bissu yang tersisa. Para pesintas yang selamat itulah yang masih ada di era reformasi sekarang ini. Mereka memang tak lagi diburu oleh rezim tertentu, tapi tetap menghadapi tantangan yang tak kalah berat, era modern.
 Sejarah Bissu dan wajah komunitas Bissu di era modern diungkapkan secara jelas oleh Farid Makkulau, yang menulis buku Potret Komunitas Bissu di Pangkep (Diterbitkan oleh Pemkab Pangkep, 2006) dan buku Manusia Bissu (Pustaka Refleksi, 2007). Pusat komunitas Bissu yang tersisa kini berada di Segeri, Pangkep, sekitar 70 km di utara Kota Makassar atau sekitar 30 km dari Pangkajene, ibukota kabupaten.
Sejarah Bissu dan wajah komunitas Bissu di era modern diungkapkan secara jelas oleh Farid Makkulau, yang menulis buku Potret Komunitas Bissu di Pangkep (Diterbitkan oleh Pemkab Pangkep, 2006) dan buku Manusia Bissu (Pustaka Refleksi, 2007). Pusat komunitas Bissu yang tersisa kini berada di Segeri, Pangkep, sekitar 70 km di utara Kota Makassar atau sekitar 30 km dari Pangkajene, ibukota kabupaten.Berbeda dengan kalangan peneliti pada umumnya, Farid yang mengaku banyak bersosialisasi dengan para Bissu, tidak terlalu setuju dengan istilah gender ke-5 bagi para Bissu. Ia mengistilahkan ada disconnect soal gender ke-5 ini. Sebab komunitas eksklusif ini hanya dapat dipahami secara utuh dengan cara tertentu dan dalam waktu yang lama.
Bagi Farid, Bissu umumnya berangkat dari kondisi waria (calabai), tak bisa sepenuhnya lepas dari kondisi kewariaannya, begitu pula pergaulannya. Informasi tentang latar belakang sosial, sikap dan perilaku Bissu hanya dapat diketahui dari kawan-kawan sepergaulannya dari komunitas calabai. Bissu tak hanya bergaul dengan sesama Bissu, tetapi di luar tradisi kebissuannya, malah lebih banyak bergaul dengan waria.
Intinya, menurut Farid, Bissu tidak sesuci seperti yang selama ini banyak ditulis peneliti. Informasi tentang pergulatan psikologis dan perilaku seksualitas menjadi tertutup karena umumnya peneliti hanya fokus pada Bissu itu sendiri, kesetiaannya berbudaya sebagaimana konsep atturiolong (tata cara leluhur), seni tari maggiri’-nya, kemampuannya berbahasa Bugis kuno dan membaca lontaraq, pusaka bissu, dan lain sebagainya.
 Meski ketahanan masing-masing Bissu berbeda-beda dalam menghadapi godaan perilaku seks menyimpang, paling tidak, tesis bahwa Bissu sebagai manusia suci yang terhindarkan dari perilaku seks menyimpang, menurut Farid harus dimentahkan karena tidak berlaku umum dan permanen.
Meski ketahanan masing-masing Bissu berbeda-beda dalam menghadapi godaan perilaku seks menyimpang, paling tidak, tesis bahwa Bissu sebagai manusia suci yang terhindarkan dari perilaku seks menyimpang, menurut Farid harus dimentahkan karena tidak berlaku umum dan permanen.“Bagaimanapun, Bissu tetap manusia biasa. Secara kodrati, mereka dilahirkan hanya dalam dua gender. Apakah kelak menjadi calabai atau calalai lebih disebabkan karena pengaruh faktor lingkungan yang membentuknya. Bissu tidak selalu merupakan kondisi permanen. Bissu adalah pilihan hidup bagi mereka yang merasa mendapat bisikan dan panggilan hidup menjadi Bissu,” begitu tulis Farid.
Boleh jadi, pengamatan Farid itu lebih banyak mengenai kondisi Bissu di era modern. Seperti ia akui sendiri, kebissuan bisa terkotori ketika banyak hal yang tidak sepantasnya ia lakukan kemudian ia perbuat dengan sadar. Desakan arus modernisasi zaman sangat memungkinkan hal ini, ketimbang di era ketika atribut-atribut modern belum menyentuh mereka.
Terlepas dari kondisi terkini, satu persatu Bissu yang tersisa di Pangkep sudah meninggal dunia. Setahun setelah Puang Matoa (pemimpin tertinggi) Bissu Saidi, Puang Lolo (pemimpin muda) Bissu yang dijabat Puang Upe, juga meninggal pada September 2012. Berselang tujuh bulan, salah seorang Bissu senior laionnya, Wa’ Nure pun menyusul kedua rekannya.
Para Bissu senior yang disegani itu meninggalkan komunitas mereka yang kian tertaih-tatih mempertahankan tradisi dan kepercayaan masa silam. Kesepakatan Dewan Adat Segeri kemudian mengangkat Juleha, salah seorang Bissu muda untuk memangku jabatan pemimpin komunitas, dengan gelar Puang Matoa.
Bagi sebagian masyarakat Pangkep, Bissu memang tak lagi sepenting dulu. Terlebih ketika masyarakat sudah banyak yang meninggalkan kebiasaan lama, seperti massanro (meminta bantuan pengobatan ke Bissu), assuro cini’ (meminta ramalan kepada Bissu mengenai masa depan), atau maggiri’ (ritual dan upacara keselamatan), dan lain sebagainya.
 Dua bulan sebelum meninggal, Puang Upe masih sempat mementaskan Tarian Mabissu, tarian penghormatan pada dewata, pada 8 Juli 2012 di Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta. Usai pementasan, Puang Upe telihat risau ketika menceritakan regenerasi para bissu di masa mendatang, meskipun ia tetap yakin bahwa panggilan-panggilan gaib akan terus mendatangi calon-calon Bissu berikutnya.
Dua bulan sebelum meninggal, Puang Upe masih sempat mementaskan Tarian Mabissu, tarian penghormatan pada dewata, pada 8 Juli 2012 di Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta. Usai pementasan, Puang Upe telihat risau ketika menceritakan regenerasi para bissu di masa mendatang, meskipun ia tetap yakin bahwa panggilan-panggilan gaib akan terus mendatangi calon-calon Bissu berikutnya. Ia merisaukan masyarakat lokal di daerahnya yang semakin jarang memesan mereka dalam ritual-ritual adat. Ia bertanya-tanya, “apakah masyarakat di zaman ini sudah lupa pada dewata yang sudah memberi hidup?”
“Saat ini kami tidak lagi diistimewakan. Kami tidak lagi hidup mewah bersama raja, melainkan harus hidup mandiri dengan menunggu sumbangan masyarakat yang akan menyelenggarakan adat. Tapi upacara ritual pun kini sangat jarang diadakan,” keluh Puang Upe dalam bahasa Bugis sopan.
Ia mengungkapkan, jumlah Bissu menyusut drastis bukan hanya karena tidak ada regenerasi. Para Bissu yang ada sebagian dibunuh dan sebagian lagi melepaskan atribut Bissu untuk berpindah ke profesi lain seperti petani atau perias pengantin.
Hingga kini, tercatatat hanya ada 12 orang Bissu di mana yang aktif hanya tujuh orang. Zaman terus menggerus mereka. Modernisasi kian meminggirkan mereka. Tradisi dan budaya kuno mereka, memupus ditelan waktu. Kelak, generasi mendatang hanya bisa mengenal Bissu lewat goresan sejarah.
Aksi Sang Waria Sakti
 Kaum Bissu di era modern kerap dinamakan Waria Sakti. Disebut waria karena sepintas kebanyakan dari mereka adalah pria secara biologis, namun berperilaku lemah lembut seperti wanita. Namun jangan tertipu, karena mereka ini dianggap orang-orang sakti setengah dewa yang mampu berkomunikasi dengan roh leluhur dan menjadi perantara manusia dengan dewa. Kesaktian mereka biasanya dipertontonkan kepada khalayak dalam sebuah upacara adat mappalili’ (turun sawah).
Kaum Bissu di era modern kerap dinamakan Waria Sakti. Disebut waria karena sepintas kebanyakan dari mereka adalah pria secara biologis, namun berperilaku lemah lembut seperti wanita. Namun jangan tertipu, karena mereka ini dianggap orang-orang sakti setengah dewa yang mampu berkomunikasi dengan roh leluhur dan menjadi perantara manusia dengan dewa. Kesaktian mereka biasanya dipertontonkan kepada khalayak dalam sebuah upacara adat mappalili’ (turun sawah). Salah satu syarat dalam upacara tersebut adalah ritual maggiri' (mengiris) yang dilakukan di rumah arajang, rumah tempat benda-benda pusaka kerajaan disimpan dan dijaga, sekaligus rumah kediaman para Bissu. Ritual maggiri’ dilakukan selama tiga malam secara berturut-turut, didahului membakar dupa di depan Arajang.
Salah satu syarat dalam upacara tersebut adalah ritual maggiri' (mengiris) yang dilakukan di rumah arajang, rumah tempat benda-benda pusaka kerajaan disimpan dan dijaga, sekaligus rumah kediaman para Bissu. Ritual maggiri’ dilakukan selama tiga malam secara berturut-turut, didahului membakar dupa di depan Arajang. Ketika gendang tradisional mulai ditabuh bertalu-talu dengan irama mistis, para Bissu dipimpin Puang Matoa (pimpinan Bissu) mulai berdiri dan menari. Nyanyian bahasa orang langit (torilangi) pun dilantunkan Puang Matoa mengiringi irama gendang.
Tatkala tempo dan suara gendang semakin keras dan cepat, satu persatu Bissu mulai memasuki kondisi trance, mencabut keris, dan mulai menusuk-nusuk dan mengiris-ngiris bagian tubuh vital mereka, seperti telapak tangan, perut, hingga tenggorokan. Dan tebakan Anda benar, benda-benda tajam itu tak mampu melukai mereka.
Artikel ini dimuat pada majalah Men's Obsession Edisi 117, Oktober 2013
Add to Flipboard Magazine.
Tulis Komentar:
Komentar:
Popular

Wanita Muslim yang Menginspirasi Dunia
24 July 2014
Film-film Islam Terbaik Sepanjang Masa
01 July 2013







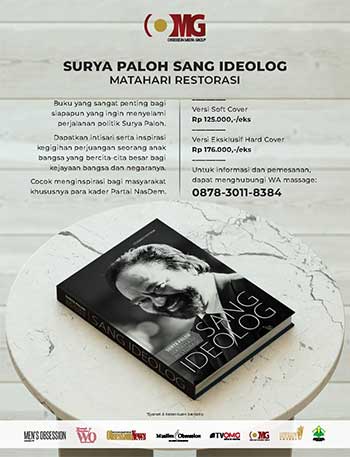

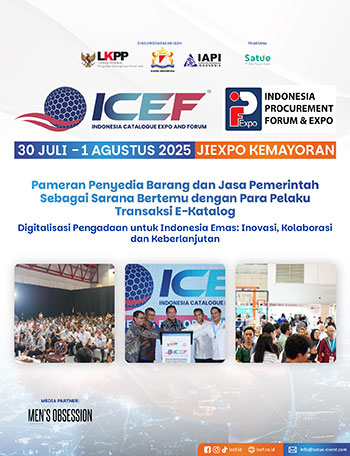












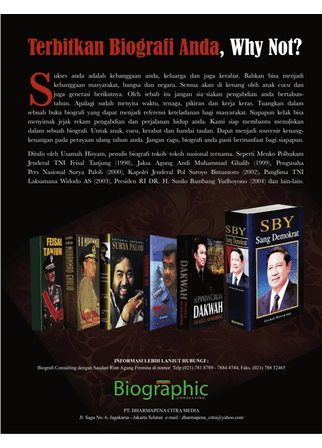
tutut nursaiful
08 October 2013